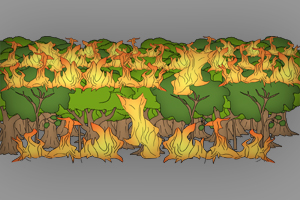Subagio S. Waluyo
Seandainya negara-negara berkembang dapat memecahkan masalah mereka dengan lebih baik; seandainya mereka memiliki pemerintahan yang jujur, tidak punya kepentingan-kepentingan terselubung, memiliki perusahaan yang lebih efisien, tenaga kerja yang lebih berpendidikan; seandainya mereka tidak mengalami semua penderitaan akibat kemiskinan—maka mereka dapat mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi tersebut secara lebih baik.
(Joseph E.Stiglitz, Making Globalization Work, 2007:119)
“…dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.”
(Penjelasan Atas UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025)
Kemarau tahun ini sama dengan tahun-tahun lalu diwarnai dengan kebakaran hutan di sejumlah tempat di Indonesia. Provinsi Riau masih setia menjadi pelanggan kebakaran hutan. Kebakaran hutan tahun ini terbilang besar karena ada 328.000 Ha hutan yang terbakar. Dari jumlah tersebut ada 28.000 Ha hutan yang benar-benar ada pohonnya. Selebihnya, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rafless Brotestes Panjaitan, adalah hutan yang tidak ada pohon (https:// nasional. kompas.com/read/2019/ 09/24/19304331/klhk-sebut-kebakaran-hutan-di-sumatera-dan-kaliman-tan-tak-bakar-vegetasi).Terlepas dari ada tidak adanya pohon, efek dari kebakaran hutan jangan dianggap remeh. Ditinjau dari segi kesehatan saja jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sampai dengan September mencapai 919.516 orang (https://nasional.kompas.com/ read/ 2019/ 09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-ispa -akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan). Itu baru dari segi kesehatan. Bagaimana dengan kerusakan lingkungan dan ekonomi?
Peristiwa kebakaran hutan yang melanda sebagian wilayah di Indonesia ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup masih jauh dari yang kita harapkan. Selama kurun waktu lima tahun (2014-2019) saja luas hutan yang terbakar 4.087.000 Ha. Dari jumlah tersebut kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2015 sebanyak 2,6 juta Ha hutan terbakar (https://databoks. katadata. co.id/ datapublish /2019 /09/16/berapa-luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia).Hutan-hutan kita yang ter-bakar itu ternyata ada pelaku-pelakunya. Ada sebanyak 14 perusahaan dan 323 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan tahun ini (https://nasional.kompas.om/ read /2019/09/24/17294681/per-selasa-14-perusahaan-jadi-tersangka-keba-karan-hutan-dan-lahan). Berarti ada unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan di Indonesia. Tahun-tahun lalu juga sama selalu ada orang atau perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan. Yang jadi pertanyaan, kenapa peristiwa sejenis selalu saja berulang?
Keterlibatan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang melakukan pembakaran hutan jelas menunjukkan ketidakberhasilan negara kita dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang giat kita laksanakan ternyata telah menciptakan manusia Indonesia yang jauh dari rasa kemanusiaan. Boleh jadi pembangunan yang diterapkan di negara ini cenderung pada perkembangan ekonomi an sich, yaitu produk barang dan jasa dari masyarakat dengan indikator pendapatan, Gross National Product (GNP) atau produk nasional bruto, Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto, dan lain-lain (Syahyuti, 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian, 2006:168). Akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menciptakan berbagai kebijakan ekonomi liberal atau ekonomi kapitalis yang dianut oleh hampir sebagian besar bangsa di dunia, termasuk Indonesia, yang telah membawa malapetaka kemanusiaan, yaitu terjebak pada dimensi keserakahan yang akut. Selain itu, pembangunan ekonomi berlangsung tanpa pertimbangan moral, tanpa memperhitungkan dampak kerusakan pada sektor nonekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi seakan akan didorong oleh nafsu serakah, mengejar profit lebih banyak, lebih besar, dan lebih tinggi sehingga unsur-unsur manusiawi cenderung disepelekan (https: //www. tubasmedia.com/ mainstream-ekonomi-baru-yang-tidak-serakah/#.XZdOp1pR3IU). Apa akibatnya? Akibatnya seperti sekarang ini, orang demikian mudah membakar hutan karena ada anggapan hutannya sudah tidak lagi produktif. Atau memang ada kesengajaan menggantikan lahan hutan dengan perkebunan kelapa sawit. Ini mentalitas bangsa kita yang mengarah pada mentalitas menerabas atau boleh juga mentalitas yang tidak bertanggung jawab.
Kalau mentalitas menerabas dan tidak bertanggung jawab masih bercokol di kalangan bangsa kita, sampai kapanpun negara kita tidak akan bisa mewujudkan seperti yang dicantumkan di atas.
“…dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.”
Kita pesimis di tahun 2025 bisa menata kembali berbagai masalah yang muncul di bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA) karena SDA kita telah dieksplorasi habis-habisan oleh bangsa-bangsa asing. Sementara yang bisa menikmatinya segelintir orang yang memang mereka itu kalangan penguasa dan pengusaha negeri ini. Kita juga pesimis bangsa ini bisa mengelola sumber daya manusia (SDM) karena pemimpin negara ini lebih cenderung mendidik bangsa ini menjadi bangsa tukang atau boleh juga bangsa kacung. Pemimpin bangsa ini lebih cenderung mendidik anak bangsa ini menjadi orang-orang yang konsumtif bukan produktif. Dengan peristiwa kebakaran di tahun 2019 ini walaupun dibandingkan dengan tahun 2015 jauh lebih kecil tapi kita juga pesimis kalau bangsa ini bisa menata pengelolaan lingkungan hidup. Dalam lima tahun terakhir saja luas hutan yang terbakar mencapai 4.087.600 Ha.(https://databoks.kata data. co.id/datapublish/2019/09/16/berapa-luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia). Apakah bisa diharapkan dengan sisa waktu yang kurang dari enam tahun dari sekarang ini sampai dengan tahun 2025 bangsa ini bisa mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan SDA, SDM, dan lingkungan hidup?
Kalau perilaku penguasa bangsa ini (yang sebagian boleh jadi juga pengusaha yang berjiwa kapitalis dan berperilaku liberalis) masih melekat dalam dirinya jiwa pengusaha, rasa-rasanya cukup sulit bagi negara ini untuk mengejar ketertinggalannya. Mana mungkin bisa menyelesaikan masalah bangsa kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang kapitalis yang liberalis? Mereka tentu sangat mengedepankan kepentingan pribadi. Mereka tidak akan mungkin memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Mereka lebih mengedepankan egonya. Bahkan, sangat mungkin karena masih ada prinsip `aji mumpung`, bisa saja kekuasaan digunakan untuk penumpukan kekayaan yang bisa digunakan tujuh turunan. Bukankah di negara ini penguasa-penguasa terdahulu lebih mengutamakan keturunan? Penguasa yang sekarangpun jangan-jangan sama. Kurang peduli dengan nasib anak bangsa yang kondisinya masih banyak yang teralienasi. Boleh jadi juga tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tujuh belas butir cuma dipandang sebelah mata. Coba kita amati gambar tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan di bawah ini.

(https://images.app.goo.gl/VaWxdMGcPt2HMDV2A)
Dari gambar di atas, dapatkah kita menjamin di tahun 2025 negara kita sesuai dengan gambar di nomor 1, 2, dan 3 menjadi negara yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan juga kehidupan sehat dan sejahtera? Penguasa negara ini (termasuk sebagian besar penguasa di daerah entah gubernur, walikota, atau bupati) tampaknya kurang punya perhatian terhadap masalah kemiskinan, kelaparan, dan kehidupan sehat dan sejahtera. Silakan kalau ada yang mau menilai di kota besar seperti Jakarta saja masih ada orang yang tinggal di pinggiran rel kereta api (KA). Saking tidak ada tempat tinggal yang layak mereka tidur di pinggiran rel KA sementara ada KA yang lalu-lalang di sebelahnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar di atas juga mencerminkan kehidupan orang-orang miskin di Jakarta yang sampai saat ini belum tersentuh kesejahteraannya. Kita tidak bisa memungkiri hasil penelitian yang dilakukan Bank Dunia bahwa urbanisasi yang dilakukan oleh banyak anak bangsa di negara ini belum tentu bisa meningkatkan kesejahteraannya. Bisa saja di negara-negara lain (Cina dan negara-negara Asia Timur dan Pasifik misalnya) orang yang ubanisasi bisa meningkat kesejahteraannya. Tapi untuk kasus di Indonesia tidak demikian. Boleh jadi mereka yang urbanisasi ke kota-kota besar justru menambah jumlah orang miskin karena sulitnya mencari nafkah. Akhirnya, di kota-kota besar muncul berbagai masalah sosial yang ditandai dengan polusi udara, kemacetan lalu-lintas, dan meningkatnya masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.
Jakarta – World Bank (WB) alias Bank Dunia mengungkapkan bahwa laju urbanisasi yang terjadi di Indonesia belum membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia merata.
Padahal, catatan Bank Dunia bahwa setiap 1% pertumbuhan urbanisasi di perkotaan mampu mendorong produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,4%. Angka ini, ternyata masih rendah dibandingkan China yang mampu mendorong 3% PDB per kapita dari persentase pertumbuhan urbanisasi sebesar 1%. Sementara negara-negara di Asia Timur dan Pasifik lainnya yang mencapai 2,7% terhadap PDB per kapita.
“Tidak setiap orang bisa mendapatkan manfaat kesejahteraan dan kelayakan huni yang dihasilkan urbanisasi,” kata Global Director for Urban and Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience Bank Dunia, Sameh Wahba di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 151 juta orang atau 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Angka ini meningkat drastis dibandingkan pada tahun 1945 atau pertama kali urbanisasi dilakukan, yaitu hanya satu dari delapan orang yang tinggal di perkotaan.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, tingkat kesenjangan di kawasan pedesaan non metro masih 43% lebih rendah daripada daerah inti metro DKI Jakarta pada tahun 2015. Kesejahteraan di kawasan pinggiran pedesaan dan perkotaan non metro juga rendah, masing-masing 35% dan 27% lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta.
Begitu juga dengan kawasan-kawasan pinggiran perkotaan yang hanya 7% lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Sehingga, masih tercatat adanya disparitas kesejahteraan.
“Masih ada kesenjangan kesejahteraan,” ujar dia.
Menurut Sameh, akibat dari kesenjangan tersebut berdampak pada sejumlah hal yang ada di perkotaan. Seperti polusi udara, kemacetan lalu-lintas, hingga meningkatnya penduduk Indonesia yang tinggal di permukiman kumuh.
Kalau sampai saat ini masih belum bisa mengatasi ketiga hal di atas, apakah negara ini bisa menjawab pernyataan Joseph E. Stiglitz bahwa untuk mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi, negara-negara berkembang memiliki pemerintahan yang jujur, yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan terselubung, memiliki perusahaan yang lebih efisien, dan SDM yang lebih berpendidikan” Selain itu, mereka juga tidak mengalami semua penderitaan akibat kemiskinan? Jujur saja, negara ini masih dipimpin oleh penguasa yang masih diragukan integritasnya.
Seandainya negara-negara berkembang dapat memecahkan masalah mereka dengan lebih baik; seandainya mereka memiliki pemerintahan yang jujur, tidak punya kepentingan-kepentingan terselubung, memiliki perusahaan yang lebih efisien, tenaga kerja yang lebih berpendidikan; seandainya mereka tidak mengalami semua penderitaan akibat kemiskinan—maka mereka dapat mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi tersebut secara lebih baik.
(Joseph E.Stiglitz, Making Globalization Work, 2007:119)
Mereka masih punya agenda terselubung karena ada di antara mereka masih ada penyakit `aji mumpung` yang dilapisi dengan baju kapitalisme dan liberalisme. Keinginan untuk mewujudkan anak-anak bangsanya menjadi orang-orang yang lebih berpendidikan masih jauh dari harapan karena memang ada kesengajaan agar anak bangsa ini tidak cerdas. Buktinya, masyarakat jelata masih banyak yang sulit menikmati pendidikan bermutu. Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah ternyata tidak efektif. Buktinya banyak keluhan yang disampaikan warga terkait yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri. Mereka juga tidak sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah swasta sehingga tidak mustahil kalau anak-anak mereka menjadi anak-anak putus sekolah.
indopos.co.id – Radi Abdul Muad, seorang anak janda miskin warga Kampung Alun Alun, Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten tampak pasrah menerima kenyataan. Sistem Zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 20/2019 atas revisi dari Permendikbud No 51/2018 dianggap bisa mengancam kelanjutan pendidikannya. Remaja berusia 16 tahun itu terancam putus sekolah. Ini lantaran dia tidak bisa masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. Ini karena terbentur jarak kediamannya dengan SMA negeri yang ada di kecamatan tempat tinggalnya, sedangkan untuk sekolah ke swasta orang tuanya tidak mampu untuk membiayai.
”Saya tidak punya pilihan lain selain sekolah negeri. Satu-satunya sekolah negeri yang dekat dari sini itu (rumahnya, Red) hanya SMA Negeri 1 Warunggunung. Sementara sekolah SMK (kejuruan, Red) negeri belum ada,” terang Enjum, 54, ibunda Radi kepada INDOPOS, Selasa (2/7/2019).
Radi yang tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ini mengaku pesimistis akan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lantaran terbentur dengan Sistem Zonasi tersebut. ”Jarak sekolah yang paling dekat dari sini hanya SMAN 1 Warunggunung sekitar empat kilometer (km), sedangkan ke SMAN 1 dan SMAN 3 Rangkasbitung atau ke SMAN 1 Cibadak berjarak hampir 10 km dari sini,” ungkap Enjum.
Perempuan yang tinggal di rumah sangat sederhana ini mengaku tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, mengingat ekonominya yang sangat terbatas. ”Boro-boro untuk ke sekolah swasta, untuk makan sehari-hari saja kami masih kekurangan,” cetus Enjum.
Meski demikan Radi masih sangat berharap dapat diterima di sekolah negeri lantaran ingin melanjutkan pendidikan. Namun karena adanya Sistem Zonasi ini dirinya hanya bisa pasrah. ”Mau bagaimana lagi, untuk ke sekolah swasta orang tua saya tidak mampu untuk membiayai,” ujarnya yang sering meraih juara kelas di SMPN 1 Warunggunung ini.
Radi ternyata tidak sendirian, rekan sebayanya Rahmat yang juga warga Kampung Alun Alun, Desa Selaraja juga tidak diterima menjadi peserta didik dalam PPDB 2019 di SMAN 1 Warunggunung. Ini karena dia terbentur jarak kediamannya dengan SMA negeri yang ada di daerah tersebut. ”Anak saya selalu menjadi juara kelas di SMPN 1 Warunggunung. Tapi karena Sistem Zonasi seperti ini akhirnya anak saya tidak diterima di SMAN 1 Warunggunung yang berjarak sekitar 4 km dari sini,” ungkap Suryana, 40, orang tua Rahmat yang juga sopir angkutan kota (angkot) kepada INDOPOS.
Yana, sapaannya mengaku tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. ”Kalau ke sekolah swasta kan harus bayar uang pangkal dan SPP, belum lagi biaya ini dan itu.Tapi kalau sekolah negeri katanya gubernur sudah digratiskan,” ungkapnya.
Dia berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga miskin yang jarak rumahnya jauh dari SMA negeri. ”Mungkin buat orang kaya tidak masalah bisa ke sekolah swasta, tapi bagi kami boro-boro untuk bayar biaya ini dan itu, untuk makan setiap hari saja pas-pasan,” tukasnya.
Yana mengaku jika anaknya tetap tidak bisa diterima di sekolah negeri, maka akan mengajarkan anaknya untuk menjadi sopir angkot seperti dirinya. ”Paling anak saya diajarin nyopir aja. Untuk masuk SMA negeri tidak mungkin, karena tidak ada sekolah negeri yang dekat. Semuanya rata-rata berjarak 5 hingga 10 km dari rumah,” katanya.
Sama halnya dengan Holil, warga Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, anaknya yang selalu menjadi juara umum dan peraih rangking di SMPN 1 Warunggunung gagal masuk SMA negeri karena jarak rumahnya mencapai 6 km. Sementara untuk ke sekolah negeri di Kota Rangkasbitung juga berjarak hampir 6 km.
Padahal, lanjut Holil, anaknya pernah mewakili Kecamatan Cibadak dalam MTQ Tingkat Kabupaten Lebak. ”Sekarang percuma punya anak pintar kalau rumah jauh dari sekolah favorit. Dengan sistem seperti ini pasti tidak akan diterima. Biar punya anak bodoh, tapi kalau rumah dekat dengan sokolah favorit pasti diterima,” ujarnya yang terpaksa menyekolahkan anakya ke salah satu sekolah swasta di Rangkasbitung.
Apakah dengan banyaknya anak-anak yang terpaksa putus sekolah kita masih bisa meningkatkan intelektual mereka kalau di lapangan terbukti seperti yang diberitakan di atas? Apakah kalau masih ada banyak kepentingan terselubung di kalangan penguasa yang diragukan integritasnya ditambah lagi dengan perusahaan yang jelas-jelas tidak efisien bisa diwujudkan enam tahun lagi negara ini bisa mengejar ketertinggalannya? Apakah kalau masih banyak anak bangsa ini yang menderita akibat kemiskinan dapat benar-benar mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi? Silakan orang-orang yang bisa berpikir jernih, yang masih ada kejujuran di lubuk hatinya menjawab semua pertanyaan tersebut. Kalau memang tidak bisa, hibur saja hati ini dengan ingat pada Sang Pencipta. Bukankah dengan ingat pada Sang Pencipta hati menjadi tenang?
Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram
(Surat Ar-Raad:28)